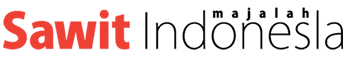Penulis: Rosediana Suharto, M.Sc. PhD*
Pada akhir-akhir ini banyak sekali diskusi mengenai minyak sawit Indonesia, terkait dengan standar sistem Sertifikasi ISPO yang lama sesuai dengan Permentan Nomor 11/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Palm oil Certification System dan berkaitan Perpres No. 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Kebun Sawit Berkelanjutan Indonesia ( ISPO baru ), tanggapan yang paling menarik yang muncul beberapa hari yang lalu mengenai ISPO berjudul “A False Hope?“ yang ditulis oleh suatu organisasi di Inggris, Environment Investigation Agency EIA, bekerjasama dengan LSM Indonesia Kaoem Telapak. Tulisan yang terbit tanggal 7 Juli 2020 di Harian KOMPAS mengenai ISPO “ Indonesia Sustainable Palm Oil dan Legalitas Sawit Rakyat “ oleh Irfan Bakhtiar, Direktur Progam Kelapa Sawit Berkelanjutan – Yayasan KEHATI, sebenarnya Yayasan KEHATI berperan besar dalam menyiapkan ISPO baru . Tulisan lainnya ialah “ 6 Tahun ISPO” oleh Forest Watch Indonesia. Banyak tulisan dan diskusi lain yang telah dipublikasikan namun masalah pokoknya sepertinya belum terbahas.
Terbitnya ketentuan ISPO yang baru, sudah sangat ditunggu karena ISPO 2015 sangat terikat dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku namun basis penyusunanya tetap berdasarkan tiga elemen sustainability, yaitu Environment Sosial, dan Ekonomi. Transparansi juga terdapat pada beberapa Kriteria dan indikator. Apabila ketentuan ISPO baru ingin lebih maju dari Permentan Nomor 2015 maka tujuan dari tiga element tersebut harus ditingkatkan untuk pencapaian Three Bottom Line yang dikenal sebagai 3P’s, People, Planet and Profit atau kadang juga disebut Prosperity, Planet dan Profit.
Standar Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 2018 terkait dengan Supply Chain Certification telah menerapkan 3 P’s ini yang diharapkan minyak kelapa sawit (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO) yang diproduksi dan diperdagangkan akan mensejahterakan manusia, menjaga lingkungan dan ekosistem serta perusahan memperoleh profit yang memadai agar usahanya dapat tetap berkelanjutan.
Memahami Standardisasi dan Standar Sesuai UU No. 20/2014
Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan.
Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
Apakah ISPO yang baru menstandarkan produk?
Judul dari Perpres Nomor 44/ 2020 adalah Sistem Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan atau dalam bahasa inggris Indonesia Sustainable Oil Palm Plantations Certification System. Ini berarti bukan produknya yaitu CPO dan PKO tetapi yang diatur adalah kebun sawit yang berkelanjutan /sustainable. Untuk itu perlu disusun suatu sistem sertifikasi CPO dan PKO yang sustainable.
Di dalam standar Uni Eropa yaitu Renewable Directive, Sustainability Criteria disusun berdasarkan lahan yang digunakan menanam tanaman untuk bahan baku biofuel. Tetapi produk yang dihasilkan membawa emisi dari dari penggunaan lahan (Land Use Change) dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) total dari kegiatan produksi juga dihitung sebagai saving emission.
Dampak Perpres Nomor 44/2020 Terhadap Usaha Petani Kecil/Swadaya
Petani swadaya umumnya memiliki kebun dengan luas 2 Ha kurang atau lebih, sulit untuk mereka menerapkan ketentuan sustainability terutama karena pada umumnya petani tidak memiliki lahan tersebut dan persyaratan yang diterapkan terlalu berat.
Kepemilikan lahan berdasar Surat Keterangan Tanah (SKT) bukanlah dokumen resmi bukti kepemilikan tanah yang seharusnya diterbitkan oleh BPN atau pemerintah daerah.
Persyaratan STDB belum dapat dipenuhi oleh petani swadaya karena lahannya tidak legal, sulitnya untuk mendapatkannya karena pengertian dalam pelaksanaannya untuk tiap daerah sangat berbeda. Hasil diskusi kami dengan staf pemerintah daerah dari beberapa provinsi bahwa STDB tidak diterbitkan bila lahan yang digunakan tempat usaha tidak legal, termasuk bagi yang merambah hutan.
Mewajibkan petani untuk siap disertifikasi dalam jangka 5 tahun mendatang merupakan persyaratan yang sangat memberatkan karena masalah legalitas tidak mungkin terselesaikan dan replanting dengan bibit yang lebih baik akan sulit terlaksana.

Apa yang ingin dicapai Perpres ISPO?
Semua kebun harus disertifikasi kebun besar ataupun kebun petani kecil untuk membuktikan kebunnya sustainable? Bagaimana minyak sawit dan minyak kernel yang dihasilkan oleh kebun yang sustainable, apakah otomatis sustainable? Tentu tidak, karena input dan output dari minyak sawit (CPO) yang keluar dari pabrik dan PKO yang dihasilkan oleh crusher, sustainability-nya belum tentu sama. Ukuran sustainability dari produk yang dihasilkan ialah emisi GRK atau Saving Green House Gas Emission.
Di Indonesia banyak kebun sawit bersekala besar ataupun berskala kecil (petani plasma dan swadaya) sedangkan pengusaha sawit yang memilki kebun dan mill tidak banyak. Demikian juga pengusaha pemilik kebun yang berperan sebagai eksportir minyak sawit.
Sesuai dengan studi yang pernah dilakukan bahwa beberapa pengusaha sawit ( pemilik kebun besar ) merangkap juga sebagai eksportir. Kebun besar membeli buah atau CPO dari berbagai sumber yaitu kebun besar, swasta dan pemerintah serta membeli dari petani plasma melalui koperasi dan petani swadaya melalui perorangan atau berkelompok. Nilai sustainability dari buah atau CPO dari tiap kebun berbeda yang ditunjukkan oleh emisi GRK yaitu CO2 eq apalagi sulit sekali menuntut petani swadaya memproduksi sustainable fruits.
Apabila tujuan melakukan sertifikasi agar semua tipe kebun sawit Indonesia itu sustainable, akan susah dicapai karena petani plasma ataupun petani swadaya masih jauh untuk dari mempraktekkan sustainability.
Tujuan pembuatan standar ISPO ini juga untuk mencapai prosperity, planet and profit seharusnya tidak ada pemain yang ditinggal. Baik itu tidak kebun plasma dan juga tidak kebun swadaya yang ilegal karena mereka menggantungkan hidupnya kepada kebun sawit.
Ekspor Sawit melibatkan petani kecil atau swadaya
Saya yakin pembuat standar ISPO yang baru telah mengerti skema ekspor dengan consignment segregasi dan mass balance. Saat ini, sedikit sekali pembeli yang ingin membeli secara segregasi (100% sustainable) dimana saving emission minimum 55%, dikemas terpisah dengan minyak sawit yang tidak sustainable. Dengan pertimbangan harganya sangat mahal.
Permintaan pembeli yang paling banyak ialah percampuran sustainable dan non sustainable palmoil yang dikenal sebagai mass balance. Beberapa perusahaan besar di Eropa memilih untuk membeli minyak sawit dengan modus mass balance. Cara ini sudah diatur di dalam Permentan tahun 2015 agar sawit rakyat dapat ikut dijual di luar negeri .
Tujuannya minyak sawit produksi petani kecil tidak tertinggal dalam ekspor minyak sawit ke luar negeri dan mereka masih terjamin penghasilannya walaupun ada ketentuan baru.
Apakah ISPO dapat mengurangi deforestasi atau menerapkan sustainable free deforestation?
Standar dibuat sesuai ukuran kemampuan bangsa ini apabila ingin menaikkan kemampuan pelaku maka persyaratan di dalam standar dinaikkan setiap kali revisi standar dilakukan akan tetapi dibutuhkan bimbingan pemerintah dan pelaku usaha terkait. Standar di Indonesia masih dalam tingkat pembinaan.
Tuntutan Uni Eropa dan EIA (Inggris) bahwa ISPO harus dapat menghentikan deforestasi tidak masuk akal karena pembukaan kebun asal hutan adalah kebijakan pemerintah untuk memberhentikan dan pelakunya dikenakan penalti. Oleh karena itu, pelaksana harus institusi legal yang memiliki otoritas. Standar hanya dapat membantu memperbaiki dengan melakukan corrective actions.
Istilah sustainable free deforestation harusnya tidak berlaku karena kriteria dalam RED 2 menilai produk dari emisi GRK melalui land based sustainability criteria. Emisi tersebut harus menghitung kehilangan karbon dari hutan yang digunakan untuk kebun sawit .
Indonesia memiliki 22 tipe tutupan hutan menurut SNI 7465-2010 tentang Klasifikasi Tutupan Lahan. Walaupun definisi hutan Indonesia berbeda dengan definisi hutan Eropa. Maka, Indonesia harus memperjuangkan apa yang sudah disepakati bersama. Karena, Indonesialah yang paling mengerti keadaan hutan tropis di negeri sendiri.
*Pengamat Sawit Nasional, Tim Pembuat ISPO 2011-2015